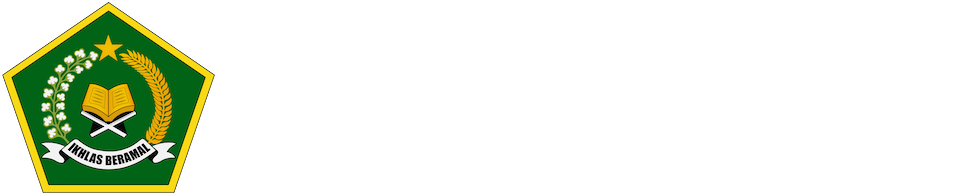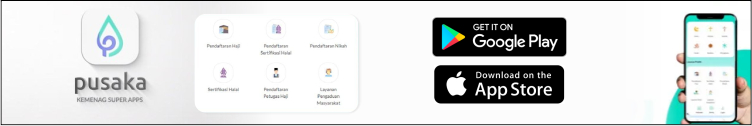Antusiasme kemusliman dalam membaca hingga mengkhatamkan Al-Qur'an khususnya di bulan suci Ramadhan merupakan rangkaian amaliah positif bernilai ibadah dan patut dicontoh. Di tataran keimanan dan psikologi manusiawi, nuansa agamis tersebut tentu saja tak lepas dari sugesti Ramadhan sebagai bulan yang kemuliaan esensinya melipat-gandakan semua bentuk-bentuk kebaikan.
Hanya saja, jika budaya membaca Ayat-Ayat Tuhan terbatas pada yang Qur'aniyah (tertulis) saja tanpa mengimbanginya dengan upaya penghayatan pada dimensi Kauniyah (semua yang terfakta) maka capaian efektifitas sosial dari budaya mengaji tidak akan bisa maksimal. Respeksitas yang pertama boleh jadi domainnya hanya bermain di seputar kepentingan mengurus pahala pribadi atau perbaikan hubungan berskala vertikal semata. Padahal, mengaji Kauniyah juga tak kalah pentingnya dilakukan lewat cara melatih hati dan pikiran untuk "membaca" fakta demi fakta kehidupan (apapun itu) yang akumulasinya bahkan meliputi kenyataan diri kita sendiri.
Antara kedua jenis Ayat-Ayat Tuhan tersebut tak hanya berfungsi saling menguatkan dan tidak bertentangan, tetapi ending-nya juga diharapkan melahirkan kesadaran natural yang meski capaiannya personal namun berefek pada kesalehan sosial (legitimasi QS. Ali Imran: 190, 191).
MEMBACA realitas alam atau makrokosmos dalam hubungannya dengan konsekuensi keberadaan diri manusia atau mikrokosmos (QS. Al-A'raf: 96, QS. Ar-Rum: 41) termasuk serba-serbi permasalahan hidup dan solusinya (QS. At-Thalaq: 2-3) mengajari kita berfikir obyektif, baik dalam posisi sebagai mahluk sosial terlebih selaku khalifah Tuhan (QS.Al-Baqarah: 30). Tentu saja kemudian, refleksi horisontalnya diharapkan berindikasi pada ketaqwaan permanen atau realitas keta'atan yang tak hanya berumur sesaat. Hal ini sejalan dengan kontekstualitas Ramadhan yang tatanan nilainya mestinya mewarnai semua skala waktu dan ruang kehidupan (sebelas bulan selainnya).
Karena itu, saat kedua cara mengaji tersebut (Qur'aniyah dan Kauniyah) bersinergi dalam membangun kesadaran beragama maka prinsip "hablun minallah wa hablun minannas" sebagai acuan dasar kemusliman diharapkan terwujud menjadi sebuah keseimbangan yang bermaslahat (individualitas yang tak menafikan urgensi sosial). Bukankah pijakan mendasar dari orientasi penghambaan manusia, esensinya mengacu pada legitimasi muatan QS. Ali Imran: 112.....???
Ushikum wanafsi bitaqwallah, Wallahu a'lam bisshawab.