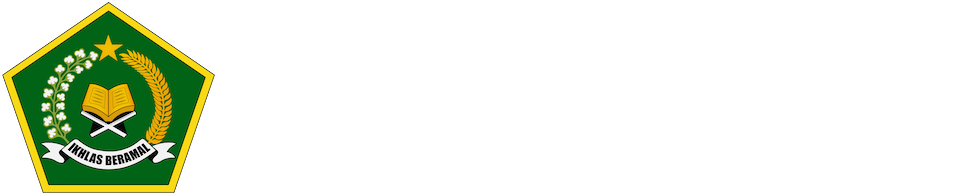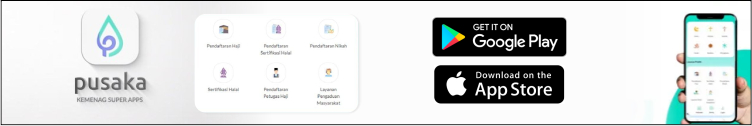Naturalitas manusia standarnya tak lepas dari keinginan untuk bisa menghargai dan ingin pula dihargai, mencintai dan ingin pula dicintai, serta hal-hal lain yang rasionalitasnya berjalan didalam konsekuensi hubungan "saling memberi dan menerima". Bawaan orisinalitas tersebut didasarkan pada prinsip dari, dengan dan untuk kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan muatan QS. Al-Anbiya': 107 terkait fungsi sosial dari keberadaan manusia.
Tendensi ego personal (apapun bentuknya) yang bahkan demi capaiannya cenderung "mengorbankan" hak orang lain secara sepihak tak hanya menjadi bagian dari kekacauan mekanisme hidup, tetapi juga merupakan tabiat murahan yang patut menjadi "bacaan berhikmah" sepanjang sejarah manusia.
Karena itu, bahasa lainnya adalah jika ada perangai kemanusiaan yang hanya ingin dihargai tapi tak belajar menghargai, hanya ingin dicintai tapi tak belajar mencintai, atau hanya tahu menerima tapi tak pernah peduli untuk bisa memberi, maka dalam konteks sosial sosoknya tergolong manusia "luar biasa" (diluar dari yang biasanya) Betapa tidak, bukankah kebiasaan-kebiasaan yang tak mengenal prinsip keseimbangan tersebut lepas dari kesepakatan moral berstandar manusiawi ?
Hal ini mengesankan bahwa tipikal manusia yang demikian seolah ingin masuk Surga "sendirian" dan tak menyadari ancaman kesepian tanpa kehadiran orang lain di dalamnya.
Puncak keluar-biasaan manusia dalam konteks keberadaan adalah ketika tugas Kekhalifahan diamanahkan Tuhan kepadanya (legitimasi QS. Al-Baqarah: 30). Hal tersebut secara otomatis memposisikannya sebagai sentral kutub bagi capaian kemaslahatan alam dan isinya. Pesan sosial ini bersinergi ketika muatan kearifan lokal pun melansir bahwa keutamaan diri sebagai manusia sesungguhnya ada pada kemampuan merealisir nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab.
Ushikum wanafsi bitaqwallah, Wallahu a'lam bisshawab.