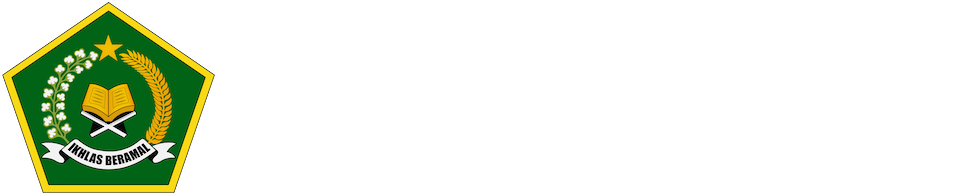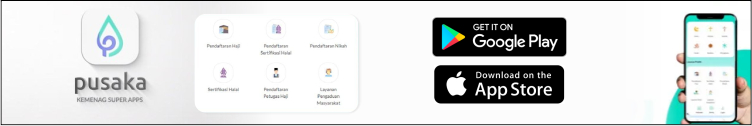Di antara fenomena sosial yang seringkali menjebak kita dalam ketidak-sadaran adalah kecenderungan spritualitas yang sedemikian "melangit" namun tak sinkron dengan fakta-fakta "pembumian" tempat kita berpijak.
Akibatnya, aksi-aksi beragama hanya terkonsentrasi pada hal-hal seremoni dan ritualitas serta kalkulasi pengejaran pahala yang sifatnya pribadi (egoisme beribadah). Disaat yang sama, dampak sosial dari keberagamaan itu sendiri menjadi sebuah ketidak-pedulian yang realitasnya "dipertanyakan".
Demi tujuan dan fungsi agama diturunkan, keinginan menggapai "Surga" di hari kemudian mestinya bersinergi dengan upaya membangun "kemaslahatan bersama" di kehidupan kita yang sekarang (standar do'a keseharian). Dengan kata lain, hakikat beragama tak hanya bersentuhan dengan harapan kebahagiaan Ukhrawi tetapi juga menjadi pengendali bagi tatanan kehidupan Duniawi dalam semua aktivitas manusia (QS. Al-Baqarah: 112, QS. Al-Qashash: 77).
Tema keseimbangan ini sesungguhnya diperkuat bahwa ketika esensi Muhammad (pada tataran tertentu) diposisikan sebagai "wasilah" menuju Tuhan, maka hal tersebut tak cukup dipahami sebatas konteks vertikalnya saja. Plus penjabaran keummatan pada sisi horisontalnya, yakni minimal dengan menjadikan diri sebagai "perantara" bagi capaian kebaikan orang lain, tentu makin memperjelas eksistensi nilai-nilai Muhammad sebagai "rahmatan lil alamin" (QS. Al-Anbiya': 107).
Terkait ini, gagasan sufistik Imam Al-Gazali sungguh tepat dan relevan. Dalam kitab Al-Munqidz Min Al-Dhalal, Ulama sekaligus filosof Islam yang tersohor itu tak serta merta memperhadapkan kita pada level "Tajalli" yang notabene wilayah prerogatif Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya terlebih dahulu kita melakukan proses pembenahan diri terkait ranah "Takhalli dan Tahalli" (urgensi akhlak sebagai syarat mendasar dari capaian nilai-nilai beragama).
Ushikum wanafsi bitaqwallah, Wallahu a'lam bisshawab.