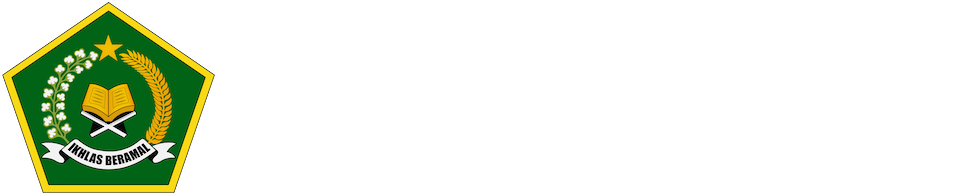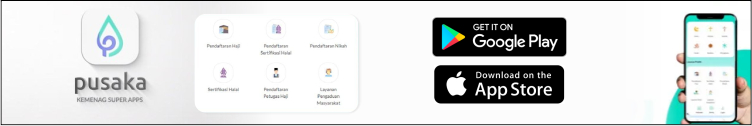Peringatan Isra' dan Mi'raj adalah seremoni keislaman yang klimaksnya mengingatkan kita tentang keutamaan shalat sebagai "sense of control" bagi kehidupan ummat Muhammad SAW.
Eksistensi shalat merupakan kewajiban yang pertanggung-jawabannya pertama kali akan ditanyakan pasca kematian manusia. Di tataran kehidupan, "shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya maka sungguh ia telah menegakkan agamanya dan barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah meruntuhkan agamanya". Demikian perkataan masyhur di kalangan para Ulama.
Namun, saat secara jujur kita bercermin pada fakta-fakta empirik ternyata harus diakui bahwa tidak semua shalat yang dikerjakan bisa diharapkan menjadi tiang agama (penuntun kehidupan). Tentu saja bukan karena esensi shalatnya, melainkan karena penghayatan nilai dari shalat tersebut yang tak mampu dimanifestasikan oleh pelakunya secara totalitas.
Disamping itu, kontekstualitas makna agama yang notabene memerlukan shalat sebagai "tiangnya" meliputi semua sisi-sisi kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa demi keseimbangan antara pengabdian personal dan aspek sosial maka persoalan keberagamaan tak cukup mengacu pada ritualitas semata. Kewajiban yang juga tak kalah pentingnya adalah apapun yang menjadi aktivitas manusia diharapkan selalu eksis dalam kendali agama (QS. Ali Imran: 112).
Di dalam shalat tak ada manipulasi karena untuk mengerjakannya, keikhlasan hati (niat) menjadi inti rukunnya. Di dalam shalat tak ada kebohongan karena kejujuran merupakan refleksi rahasia dari penghambaan manusia kepada Tuhan. Pun, di dalam shalat tak ada kebencian sosial karena esensi wudhu telah mengantarnya lewat hikmah-hikmah cinta dan kesadaran terkait relasi kemanusiaan.
Bahkan ketika prosesinya dilakukan secara berjamaah, sesungguhnya ibadah shalat telah mengajarkan nilai-nilai kebersamaan yang meliputi urgensi akhlak (etika), penyatuan orientasi sujud dan tatanan kesetaraan status sebagai hamba di hadapan Tuhan. Lebih dari itu, ketika filosofi shalat ditutup dengan ucapan "salam" ke kanan dan ke kiri, itu berarti bahwa perjuangan agar bisa berbagi kemaslahatan antar seluruh makhluk Tuhan menjadi sebuah keniscayaan. Bukankah hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari mandat kekhalifahan manusia di muka bumi (muatan QS. Al-Baqarah: 30) ?
Di saat yang sama, hikmah lain dari prosesi shalat berjamaah adalah mereka yang lebih dulu hadir di Mesjid otomatis akan berada di saf terdepan. Hal ini menyiratkan pesan bahwa barang siapa yang ingin "ditetuakan" menyangkut hal-hal sosial kemasyarakatan (analogi kepemimpinan), hendaklah ia menjadi sosok percontohan dalam menjabarkan makna-makna "sujud" kepada Tuhan. Bukankah muatan QS. Al-Hujurat: 13 melegitimasi Taqwa sebagai penentu reputasi dan capaian kemuliaan diri manusia ?.
Sebagaimana Taqwa yang keutamaannya juga disorot dalam QS. At-Thalaq: 2-3 dan QS. Al-A'raf: 96, namun finalisasi tersebut baru bisa terwujud ketika realitas hidup manusia telah dicahayai oleh esensi dan nilai-nilai shalat. Akumulasinya tentu saja memantul pada penjabaran sifat-sifat karimah seperti ikhlas, kejujuran, keadilan, persatuan, cinta kasih dan optimisme serta tatanan perilaku-perilaku agamis lainnya yang mengacu pada capaian kemaslahatan bersama (QS. Al-Anbiya': 107).
Terkait analisis ini, benarlah ketika muatan QS. Al-Ankabut: 45 menekankan tentang betapa pentingnya shalat itu "didirikan" (lebih dari sekedar mengerjakan). Ini dimaksudkan agar fungsi sosialnya menjadi perisai keselamatan diri manusia dari ancaman ragamnya perbuatan keji dan munkar. Olehnya itu, ketika kita diperhadapkan pada oknum diri sendiri sebagai pelaku-pelaku shalat yang pada dimensi sosialnya justru menjadi "dalang" dari berbagai kejahatan (baik yang nampak maupun terselubung), maka penghayatan nilai dari shalat yang kita kerjakan logis "dipertanyakan".
Ushikum wanafsi bitaqwallah, Wallahu a'lam bisshawab.