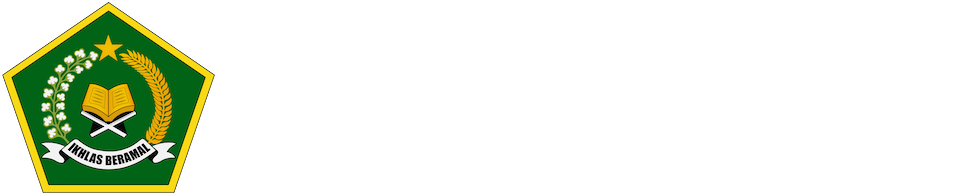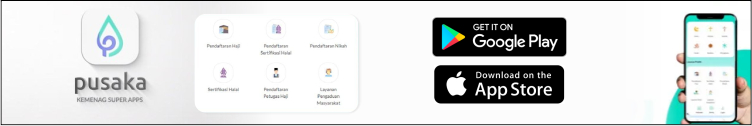Tulisan ini terutama untuk menyadarkan diri sendiri yang sangat mungkin setiap hari dalam menyikapi perbedaan tafsir-tafsir keberagamaan terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan.
---------------------------------------------------
Mari sejenak berbisik kepada diri, kita bayangkan kita sedang masuk ke sebuah rumah makan yang tempatnya luas, suasananya hangat, dan pelayannya ramah. Di dalamnya tersedia berbagai macam menu. Ada yang pesan nasi goreng, ikan, ada yang suka soto, ada pula yang hanya cukup dengan teh atau kopi pahit dan sepotong gorengan. Tak ada yang aneh. Tak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang punya lidah dan selera masing-masing. Yang penting makanannya halal, bergizi, dan tidak bikin keracunan. Begitulah seharusnya kita memandang agama, khususnya Islam. Ia adalah rumah makan besar, tempat orang-orang datang dengan niat yang sama: mengisi perut rohani, menenangkan batin, dan mencari jalan pulang.
Namun sayangnya, masih banyak dari kita yang lupa membawa etika ke dalam rumah makan itu. Alih-alih menikmati makanan masing-masing, kita malah sibuk melototi piring orang lain. “kenapa dia makan itu?” kok dia tidak pakai sambal? dan Bla..bla..
Jika sikap kita begitu, kita bukan lagi penikmat makanan rohani, melainkan pengawas dadakan yang merasa punya otoritas menilai selera orang lain. Ironis, kita lupa bahwa sejak awal tidak semua orang tumbuh dalam dapur dan resep yang sama. Bahkan lidah sendiri pun kadang berubah, apalagi lidah orang lain.
Ada yang lahir di keluarga yang menyukai masakan gurih, ada yang terbiasa dengan yang pedas. Ada yang tumbuh dalam lingkungan sufi yang penuh dzikir dan air mata, ada juga yang besar di lingkungan akademik yang penuh diskusi dan logika. Semua punya jalan masing-masing. Tapi tetap di bawah atap yang sama: atap tauhid. Anehnya, kita lebih sibuk mempertanyakan cara orang lain makan, daripada memastikan apakah makanan kita sendiri sudah bersih, halal, dan benar-benar mengenyangkan jiwa. Kita sibuk mencela gaya ibadah orang lain, padahal wudhu kita sendiri sering terburu-buru.
Hanya karena seseorang tidak memakai cara makan kita, kita merasa dia harus ditegur, dihakimi, bahkan dilarang masuk ke warung ini. Ada semacam kecenderungan ingin menyeragamkan menu. Seolah-olah semua orang harus makan nasi goreng seperti kita. Padahal Nabi sendiri memberi ruang luas untuk perbedaan. Dalam satu waktu, para sahabat berbeda pendapat soal shalat Ashar saat perjalanan, dan beliau tidak mencela satu pun dari mereka. Tapi kita hari ini lebih suci dari Nabi, lebih galak dari malaikat, dan lebih sibuk dari ulama zaman dulu.
Lebih parah lagi, sebagian dari kita bukan cuma mengawasi isi piring orang, tapi juga ikut menyuapi paksa. “Kamu harus makan ini, karena ini yang paling benar.” Tak ada dialog. Tak ada tenggang rasa. Bahkan kadang, tak ada ilmu. Hanya karena kita merasa paling kenyang, kita anggap orang lain pasti lapar. Ini bukan soal dakwah, tapi soal dominasi rasa. Kita bukan sedang menawarkan makanan, tapi memaksakan menu. Lupa bahwa tidak semua perut cocok dengan rendang yang kita anggap paling nikmat itu. Ada yang justru alergi dan malah sakit karenanya.
Maka penting untuk mengingatkan diri: selera beragama bukanlah hal yang bisa dipukul rata. Dalam Islam sendiri, ruang perbedaan itu bukan hanya diakui, tapi dirawat. Dari fiqih hingga tasawuf, dari jalur mazhab hingga corak budaya, semua berkontribusi membentuk khazanah Islam yang kaya rasa. Seperti dapur Nusantara yang punya seribu bumbu dan teknik masak, Islam pun berkembang dengan cita rasa yang berbeda di tiap tempat. Islam di Padang punya cita rasa yang berbeda dengan Islam di Madura, pun Islam di Yogyakarta tak sama dengan Islam di Bima. Tapi semua tetap Islam selama masih dalam bingkai yang sama, dengan bahan dasar yang tidak menyimpang.
Yang membuat rumah makan jadi nyaman bukan seragamnya menu, tapi suasana saling menghormati di dalamnya. Kita boleh berbeda menu, tapi tetap bisa saling sapa, senyum, dan duduk berdampingan. Begitu pula dalam beragama. Kita bisa memilih jalan yang lebih sesuai dengan nurani dan pemahaman kita, tanpa merasa perlu menginjak jalan orang lain. Agama bukan kompetisi, apalagi olimpiade rebutan gelar paling saleh. Ia adalah perjalanan panjang, dan setiap orang sedang menempuhnya dengan cara dan kecepatan masing-masing. Yang kita butuhkan bukan penghakiman, tapi pengertian. Bukan klaim, tapi pelukan.
Jadi, mari kita duduk tenang di rumah makan besar ini. Pesanlah menu yang kita sukai. Nikmatilah dengan khusyuk. Jangan ganggu orang di sebelah yang sedang menikmati makanannya. Kalau kita melihat ada yang salah, beri tahu dengan santun, seperti pelayan yang baik, bukan dengan membentak, tapi menawarkan. Jangan sampai kita sibuk mengurus piring orang, sementara piring kita kosong, dan hati kita justru kelaparan. Agama seharusnya jadi ruang kenyang rohani, bukan arena rebutan piring yang bikin semua orang saling curiga. Pada akhirnya, Tuhan tak menilai menu kita, tapi seberapa ikhlas kita menyuapinya.
Oleh : Hamzah (Guru MA Nuhiyah Pambusuang)