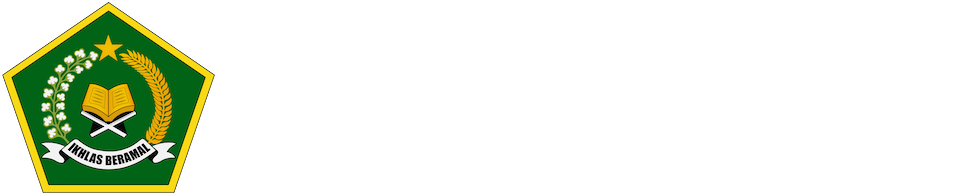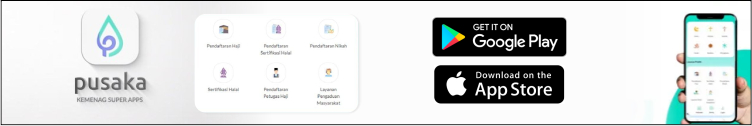Di antara fenomena sosial yang seringkali menjebak kita dalam ketidak-sadaran beragama adalah kecenderungan spritualitas yang sedemikian "melangit" namun tak berimbang dengan fakta-fakta "pembumian" tempat kita melakoni peran-peran kehidupan.
Akibatnya, aksi-aksi beragama hanya terkonsentrasi pada hal-hal seremoni dan rutinitas ritual serta kalkulasi pengejaran pahala yang muatannya lebih pada tendensi keselamatan pribadi (egoisme beribadah). Capaian beragama semacam ini seolah hanya terukur pada maraknya formalitas pengajian, serba-serbi dzikiran yang prosesinya terkesan disakralkan, dsb. Di saat yang sama, dampak sosial yang seharusnya menjadi konsekuensi logis dari ikhtiyar pemberdayaan beragama terkadang justru menjadi realitas yang "dipertanyakan".
Padahal, demi tujuan dan fungsi agama diturunkan maka keinginan menggapai "Surga" di hari kemudian mestinya disinergikan dengan upaya membangun "wujud nilainya" di kehidupan kita yang sekarang (manifestasi standar do'a keseharian). Dengan kata lain, eksistensi beragama sesungguhnya tak hanya bersentuhan dengan harapan kebahagiaan berdimensi Ukhrawi, tetapi juga menjadi tatanan-tatanan nilai kehidupan Duniawi yang dikondisikan terkait apapun aktivitas manusia (QS. Al-Baqarah: 112, QS. Al-Qashash: 77 dan QS. Ad-Dzariyat: 56).
Tema keseimbangan ini seharusnya juga diperkuat oleh prinsip kearifan bahwa ketika esensi Muhammad (pada tataran tertentu) diposisikan sebagai "wasilah" menuju Tuhan, maka hal tersebut tak cukup dipahami sebatas konteks vertikalnya saja. Plus penjabaran horisontalnya di kehidupan keummatan yakni minimal dengan menjadikan diri sebagai "perantara" bagi capaian kemaslahatan hidup orang lain, tentu makin akan memperjelas eksistensi keterikutan kita pada nilai-nilai Muhammad sebagai "rahmatan lil alamin" (QS. Al-Anbiya': 107).
Menafikan aspek ritualitas yang notabene juga penting dalam beragama akan menghambat terbangunnya hubungan kevertikalan dengan Tuhan. Akan tetapi, tanpa perimbangan pada aspek sosial maka posisi manusia berpotensi menjadi "bumerang" bahkan bertentangan dengan legitimasi keberadaannya selaku Khalifah Tuhan di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30).
Terkait ini, gagasan sufistik Imam Al-Gazali (Hujjatul Islam) sungguh tepat dan relevan. Dalam kitab Al-Munqidz Min Al-Dhalal, Ulama sekaligus filosof Islam yang tersohor ini tak serta merta mengorientasikan ikhtiyar penghambaan manusia pada capaian "Tajalli" yang notabene wilayah prerogatif Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk terlebih dahulu melakukan muhasabatun nafs atau proses pembenahan diri secara ril terkait ranah "Takhalli dan Tahalli".
Disamping kedua maqam (tahapan) mujahadah tersebut mengajarkan tentang keutamaan menghiasi diri dengan rangkaian akhlak-akhlak yang baik, juga menjadi syarat penentu bagi pengenalan hakikat diri dan subtansi nilai beragama. Bukankah ini sejalan ketika Rasul SAW berpesan bahwa "Sesungguhnya Aku diutus untuk merekonstruksi perbaikan akhlak-akhlak kemanusiaan"?
Karena itu, pendekatan "keseimbangan" ini sesungguhnya juga tercermin dalam filosofi keterkaitan tiga peralihan kata antara KHALIQ, MAKHLUQ dan AKHLAQ.
Ushini waiyyakum bitaqwallah, Wallahu a'lam bisshawab.