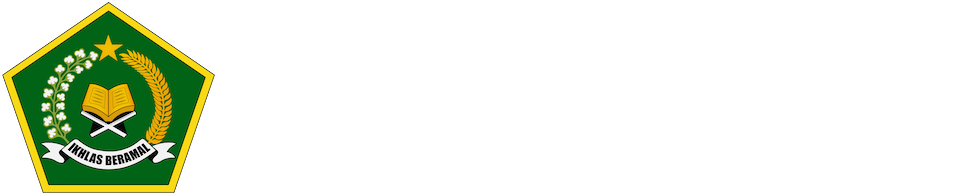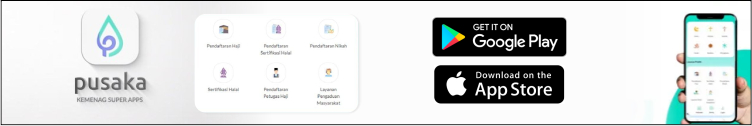HARI INI adalah Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 H. Hari di mana kita semua merayakan kemenangan setelah sebulan lamanya berjuang melatih diri lewat kewajiban berpuasa dan berbagai macam ibadah lainnya. Semoga saja perayaan kemenangan ini bukanlah kamuflase yakni sebuah situasi di mana secara formal kita melakukan sesuatu namun realitas kita yang sebenarnya di luar dari capaian itu. Hal tersebut tentu saja bergantung pada sesungguh apa ikhtiar kita dalam menjalani Ramadhan plus hidayah Tuhan yang menjadikannya sebagai bulan pendidikan taqwa.
Kehadiran Ramadhan yang formulasinya sekali dalam setahun merupakan bulan yang kemuliaannya dapat menghapus dosa-dosa kemanusiaan sepanjang kita benar-benar ikhlas memenuhi prosedurnya. Di saat yang sama, fadhilah Ramadhan juga melipat-gandakan semua bentuk kebaikan dan ibadah apapun yang dikerjakan di dalamnya. Bahkan, siklus perjalanannya menyajikan tiga fase penting yang notabene dibutuhkan oleh manusia-manusia pendosa macam kita. Tiga fase yang dimaksud adalah fasilitas rahmat di 10 hari pertama, ampunan di 10 hari pertengahan dan jaminan keterhindaran diri dari api Neraka di 10 hari terakhir. Hanya saja, meskipun akumulasi tersebut merupakan pengharapan manusiawi yang ingin kita raih namun juga bisa "membenamkan" kita dalam perspektif JANGKA PENDEK terkait legitimasi sesaat terhadap keistimewaan Ramadhan.
Jika nantinya kembali kita terluntah-luntah melakukan ibadah karena berpikir Ramadhan sudah pergi, bacaan Al-Qur'an pun tak lagi menjadi agenda penting karena bulan yang sarat dengan fasilitas tadi sudah kita anggap usai, bahkan amaliah-amaliah kesalehan lainnya dengan perlahan kita hentikan seiring berakhirnya Ramadhan, maka tidakkah ini menjadi sebuah indikasi betapa kita memposisikan Ramadhan sebatas momentum dramatisasi kesalehan sesaat ?
Situasi macam ini identik dengan kultur beragama yang secara musiman terjebak dalam euforia tahunan. Sebaliknya, jika kita menggunakan perspektif JANGKA PANJANG maka nilai-nilai Ramadhan tentu lebih kita harapkan menjadi ruh kepribadian yang "natural" di mana pengaktualisasiannya menjadi warna kenyataan diri di sebelas bulan selainnya.
Ketika rangkaian amaliah Ramadhan terkonsentrasi pada perolehan pahala semata, maka andai "iming-iming" itu tidak ada, masihkah kita menganggap ibadah itu penting plus menjadikan Tuhan sebagai sentral kebutuhan bagi kelangsungan hidup kita?.
Tidakkah ini membuktikan bahwa jangankan di ranah horisontal, di tataran vertikal pun terkesan masih sebegitu kalkulatifnya kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Padahal, kurang baik apa Tuhan pada kita. Bukankah rentetan ayat dalam QS. Ar-Rahman memperjelas bahwa dominasi nikmat-Nya yang tak terhitung telah tersalur sebegitu adilnya di kerahasiaan hidup setiap manusia ?
Oleh karena itu, pendekatan iman merupakan solusi paling efektif untuk bisa membentuk karakter kemusliman dan ketulusan mengabdi kepada Tuhan. Hal ini kemudian terhormat dalam keyakinan bahwa ketika Allah SWT mewajibkan segala sesuatu tak terkecuali perintah berpuasa maka dengan mentaatinya pasti akan mendatangkan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan kehidupan sosial. Sebaliknya, pelanggaran terhadap segala yang dilarang-Nya, cepat atau lambat pasti memperhadapkan kita pada ancaman kemudharatan bahkan kebinasaan dalam arti yang seluas-luasnya.
Betapa seringnya kita terjebak dalam kasus-kasus asusila (di semua jenis dan levelnya) yang mencerminkan "pengabaian nilai-nilai Ramadhan" pasca Idulfitri. Gagalnya kita memaknai kemenangan dalam bentuk "merdekanya diri" dari hasutan sifat serakah, culas, egoisme dan arogan serta rangkaian sifat-sifat buruk lainnya pasti menjadi sumber petaka bagi kelangsungan hidup manusia. Situasi macam ini sebagaimana yang tersirat dalam muatan QS. Ar-Rum: 41 merupakan potret sosial terkait belum efektifnya kesadaran dan penerapan nilai-nilai beragama di dalam kehidupan.
Banyak sudah kasus-kasus amoral terjadi di muka bumi, penghianatan kepercayaan, manipulasi bergentayangan bahkan ragam kejahatan lainnya yang tak lagi dianggap tabu dalam dinamika budaya manusia. Maka, di sinilah hikmah inti dari perintah berpuasa agar kemenangan sejati yang teraktualisasi lewat "pengendalian diri" jauh lebih utama dibanding kepuasan semu yang diperoleh lewat kultur saling menipu, saling memfitnah, menebar kebencian bahkan pertumpahan darah antar sesama.
Ketika term Idulfitri dimaknai sebagai hari raya KEMENANGAN bagi pelaku puasa Ramadhan, maka di manakah esensi itu saat satu persatu dari hasutan kejahatan kembali menguasai, mentaktis bahkan memasung kita dalam ketidak-berdayaan?. Ketika pasca Ramadhan, liarnya nafsu-nafsu ilegal kembali menggerogoti kehidupan, mengendalikan bahkan memangsa semua yang diinginkan meskipun bukan miliknya, maka kemanakah konsistensi air mata Ramadhan yang dengan khusyu' kita tumpahkan di momentum malam-malam pertobatan ?
Itulah sebabnya, jika secara kontekstual HARI INI adalah hari raya, maka HARI KEMARIN juga hari raya. Bahkan SETIAP HARI ketika seseorang mampu untuk setia mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menghindari apapun yang dilarang-Nya maka sesungguhnya baginya adalah capaian HARI RAYA. Statemen ini tentu saja mengacu pada legitimasi hari yang berisi kebaikan, kemuliaan dan makna-makna KEMENANGAN.
Di saat yang sama, ibadah puasa (wajib maupun sunnat) sesungguhnya tak hanya berguna bagi penyehatan fisik manusia, melainkan urgensi taqwa yang berindikasi pada penguasaan hawa nafsu lebih dibutuhkan untuk bisa mengenal "batasan-batasan" yang semestinya dalam hal apa saja. Obyektifitas nilai berpuasa akan memproduksi manusia-manusia yang "tahu diri" dan mampu memilah antara hak pribadi dan milik orang lain, serta permanennya kesabaran didalam menempuh ujian-ujian kehidupan.
Terkait ini pula, ritualitas puasa tak hanya merupakan ibadah berdimensi kemanusiaan (horisontal) tetapi esensinya juga mengajarkan sesuatu yang prinsip (vertikal). Bukankah sejengkal pun gerak manusia di ruang semesta ini tak ada yang luput dari pengetahuan Tuhan ?. Hal ini relevan ketika di dalam Hadits Qudsi Tuhan berfirman "Al-insanu sirrii wa ana sirruhu" (Manusia itu rahasia-Ku dan Aku rahasianya).
Hubungan rahasia tersebut berindikasi pada pengendalian ragamnya hawa nafsu yang tidak saja berkenaan dengan hal-hal yang "diharamkan" tetapi juga pada perkara-perkara halal sekalipun. Karena itu, demi pakaian taqwa sebagai target dari kewajiban berpuasa, tujuannya tak lain untuk mengalahkan kekuatan besar dari belenggu nafsu-nafsu nagatif diri kita sendiri. Demi stabilitas hidup dan masa depan peradaban manusia, hal inilah yang disebut Rasul sebagai PERANG TERBESAR yang harus dimenangkan.
Sisi lain yang juga terkait dengan capaian kualitas berpuasa adalah sinergisnya dengan nilai-nilai budaya Kemandaran yang mengacu pada prinsip SIPAKATAU dan bukan "Siapa Kau". Muatannya tak lain adalah kesadaran untuk saling menghargai, ikhlas berbagi dan membangun harmoni kehidupan menuju capaian kemaslahatan bersama (QS. Al-Anbiya': 107).
Tanpa kualitas taqwa sebagai buah dari pendidikan Ramadhan maka budaya-budaya mala'bi yang notabene sejiwa dengan ajaran agama mustahil bisa terwujud. Karena itu, pencapaian kemenangan di hari yang Fitri juga disugesti oleh sebait petuah leluhur Kemandaran yang berbunyi :
"Tappa' diwawa pole, Siri' dipapputiang, Rakke' di Puang iamo sulo tongat-tongan di waona lino", (kita lahir dengan Iman, realitasnya dibungkus bahasa moral, taqwa pada Tuhan itulah sejatinya obor penerang hidup di atas bumi).
Pada akhirnya, tidakkah sebaiknya kita bermuhasabah tentang kemenangan Fitri itu sebabnya apa dan indikasinya pula seperti apa.....?
Ushini waiyyakum bitaqwallah, Wallahu a'lam bisshawab.